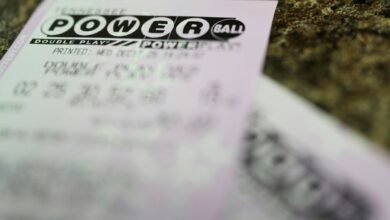Ketika keluhan menggantikan akuntabilitas

Ketika aktivis konservatif Charlie Kirk dibunuh, beberapa orang membenarkan tindakan tersebut sebagai balas dendam politik. Ketika Brian Thompson, CEO UnitedHealthcare, ditembak mati, kemarahan tersangka penembak terhadap industri asuransi kesehatan terlihat jelas seolah-olah itu adalah sebuah penjelasan.
Dalam kedua kasus tersebut, kekerasan disaring melalui keluhan dibandingkan dengan kecaman langsung.
Sebagai seorang psikoterapis yang berpraktik di New York City dan Washington, D.C., saya melihat logika yang sama di kantor saya: Beberapa orang percaya bahwa rasa sakit membuat mereka berhak untuk menyerang, atau bahwa keluhan saja yang membenarkan pilihan yang merusak. Persamaan antara psikologi individu dan budaya kita secara umum sangat mencolok—dan sangat meresahkan.
Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah kejahatan telah dilakukan, melainkan “Apakah saya bersimpati dengan keluhan yang ada di balik kejahatan ini?”
Hal ini menunjukkan adanya perubahan tajam dari masa lalu. Setelah tragedi seperti pembunuhan Presiden John F. Kennedy, pemboman Kota Oklahoma, dan serangan 11 September, masyarakat Amerika tidak memperdebatkan apakah kekerasan dapat dibenarkan. Para pemimpin dari seluruh spektrum bersikeras bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Kejelasan moral ini telah memberikan pijakan bagi negara ini.
Sebaliknya, saat ini kita terbagi ke dalam narasi-narasi yang saling bersaing. Daripada mengutuk tindakan kekerasan, kami bertanya apakah korban atau pelaku mematuhi kebijakan kami.
Tren ini meluas ke seluruh spektrum politik. Setelah serangan 6 Januari di Capitol, banyak yang menganggap para perusuh sebagai patriot, yang kemarahannya terhadap pemilu yang dicuri menjadi pembenaran atas tindakan mereka. Setelah kerusuhan perkotaan beberapa tahun terakhir, penjarahan kadang-kadang digambarkan sebagai “reparasi.” Di kampus-kampus, protes dengan kekerasan dibingkai ulang sebagai respons terhadap trauma.
Setiap contoh menunjukkan perubahan yang sama: keluhan digunakan untuk mengaburkan akuntabilitas.
Dalam praktik saya, saya telah melihat betapa korosifnya pola pikir ini. Seorang pasien pernah datang kepada saya dalam keadaan marah kepada rekan kerjanya yang telah meremehkannya di tempat kerja. Dia bersikeras bahwa dia mempunyai hak untuk menyabotase rekannya sebagai balasannya. Kemarahannya nyata, keluhannya bisa dimengerti. Namun jika saya mendukung keinginannya untuk membalas dendam, saya pasti terlibat dalam penghancuran dirinya. Perawatan tersebut hanya berhasil karena dia menyadari bahwa rasa sakitnya, meskipun sahih, tidak membenarkan menyakiti orang lain.
Pasien lain, seorang mahasiswa, menggambarkan perpisahan itu sebagai “trauma” dan mengatakan penderitaannya adalah akibat dari membolos kelas dan menyerang teman selama berminggu-minggu. Kata “trauma” memberikan legitimasi terhadap rasa sakit, namun juga memberikan pelarian dari tanggung jawab. Ketika dia menyadari bahwa kesulitan tidak membebaskannya dari pilihan, dia perlahan-lahan membangun kembali kakinya. Tanpa transformasi ini, dia mungkin akan menjadikan keluhannya sebagai alasan untuk hidup. Bahasa yang lebih mengutamakan pembenaran dibandingkan penjelasan akan menghambat pertumbuhan dan melemahkan akuntabilitas.
Kami melihat dinamika yang sama di institusi kami. Jaksa enggan mengajukan tuntutan karena takut dianggap tidak sensitif. Para jurnalis melunakkan bahasanya dengan mengganti kata “kejahatan” dengan “gangguan” atau “insiden”. Sekolah dan tempat kerja, yang ingin menghindari kemarahan, menurunkan standar dan membenarkan perilaku yang sebelumnya mereka tantang. Seiring waktu, tanggung jawab itu sendiri mulai tampak opsional.
Di media sosial, keluhan telah menjadi hal yang lazim. Postingan yang menggambarkan kemunduran pribadi sebagai bukti menjadi korban sering kali menjadi viral. Seruan untuk fleksibilitas diabaikan. Algoritma menghargai kemarahan, dan Anda tahu bahwa jika Anda menginginkan perhatian atau keringanan hukuman, atasi keluhan tersebut. Dengan melipatgandakan pesan ini ke jutaan interaksi, hal ini membentuk kembali pemahaman kolektif kita tentang perilaku yang dapat diterima.
Jawabannya bukanlah menolak penderitaan. Banyak ketidakadilan yang nyata dan patut mendapat perhatian. Namun empati tidak terkecuali. Kasih sayang harus hidup berdampingan dengan tanggung jawab. Tanpa keduanya, individu tidak bisa menjadi lebih kuat, dan masyarakat tidak bisa bersatu.
Memulihkan keseimbangan ini tidaklah mudah. Para pemimpin – politisi, tokoh budaya, dan jurnalis – dapat menjadi teladan. Mereka harus menyebut kekerasan sebagai apa adanya, bahkan ketika korbannya tidak populer atau ketika pelaku merasa simpati atas keluhannya. Universitas harus mendidik mahasiswanya bahwa protes dan perbedaan pendapat itu perlu, namun kehancuran tidak bisa dihindarkan. Jaksa harus menahan godaan untuk membenarkan kejahatan berdasarkan motif. Media harus menghindari sanitasi kekerasan dalam eufemisme terapeutik.
Sejarah memberikan petunjuk. Gerakan hak-hak sipil memperoleh kekuatan dari keluhan, namun para pemimpinnya menolak untuk membenarkan kekerasan. Kekuatan moral mereka berasal dari desakan mereka bahwa akuntabilitas yang setara di bawah hukum tidak bisa ditawar. Keseimbangan ini memberi mereka legitimasi dan kekuasaan.
Setelah lebih dari dua dekade berlatih, saya belajar betapa sulitnya memberi tahu orang-orang bahwa rasa sakit mereka tidak membuat mereka tidak nyaman. Namun saya juga melihat bahwa kenyataan pahit inilah yang menjadi titik awal penyembuhan. Amerika membutuhkan kebenaran ini sekarang.
Jonatan AlbertDia adalah seorang psikoterapis yang berpraktik di New York City dan Washington, D.C., dan merupakan penulis buku yang akan segera dirilis, “Therapy Nation.”